Saat buku-buku tentang penerjemahan sangat jarang kita temukan, sebuah karya yang mendalam tentang teori penerjemahan tercipta. Dengan apik, Benny Hoedoro Hoed, Guru Besar Emeritus pada Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia membuat terobosan baru dalam hal buku penerjemahan. Dalam buku akademiknya, yakni Penerjemahan dan Kebudayaan, ia menyisipkan sisi kebudayaan yang jarang dibahas buku penerjemahan lainnya. Hoed juga membahas secara mendalam apa yang dibutuhkan dan harus diketahui serta masalah-masalah yang sering dihadapi seorang penerjemah.
Pada bagian pendahuluan bab ini, ditulis bukan oleh Hoed, tapi Alfons Taryadi. Bagian ini memaparkan apa saja yang bisa dikaitkan dengan ihwal penerjemahan. Penjelasan pada bagian ini memberitahukan kepada kita secara ringkas tentang kendala, faktor dalam penerjemahan, pemahaman teks sumber, dan ketiadaan terjemahan sempurna.
Seusai bagian pendahuluan, Hoed memulai tulisannya dengan mengungkapkan objek terjemahan, yaitu teks. Penerjemahan, seperti disinggung pada halaman 28, adalah upaya untuk mengungkapkan kembali pesan yang terkandung dalam teks suatu bahasa atau teks sumber ke dalam bentuk teks dalam bahasa lain atau teks sasaran. Dari situ, dapat dilihat bahwa teks merupakan bahasa itu sendiri. Syahdan, yang dihadapi penerjemah adalah bahasa, tepatnya dalam kaitan ini yakni bahasa tulis, teks.
Bahasa memiliki aspek bentuk dan makna. Dalam penerjemahan, aspek makna adalah pesan yang terkandung dalam bahasa sumber, atau bahasa yang diterjemahkan. Penulisnya-lah yang menciptakan pesan tersebut. Dan di sinilah tugas penerjemah untuk dapat mengalihkan pesan tersebut ke dalam bahasa lain.
Teks terjemahan bermacam-macam. Hanya saja, ada teks tertentu yang memiliki daya tersendiri bagi masyarakat. Teks lama dan teks keagamaan. Kedua teks ini memiliki keruwetan tersendiri, karena terkandung makna konteks sosial, yang bisa memunculkan efek sensitifitas. Teks lama sangat berkaitan dengan budaya masyarakat, dan teks keagamaan berkaitan dengan kepercayaan tiap pribadi manusia.
Teks lama, seperti manuskrip-manuskrip kuno yang jarak waktu pembuatannya amat jauh dari masa kini, memang memiliki nilai sejarah. Namun, di sisi lain, teks lama ini, apapun bentuknya, jika dikaitkan dengan penerjemahan, kompleksitas masalah pragmatiknya semakin bertambah. Seperti telah disinggung di atas, tentu ini dikarenakan adanya jarak waktu pembuatan teks lama tersebut, dengan penerjemah yang hidup di masa kini.
Akibatnya, kemungkinan besar akan muncul perbedaan tafsir di antara pembuat dan penerjemah teks lama. Karena bagaimana pun, jarak waktu dan jarak budaya amat berpengaruh bagi penerjemah. Inilah yang diperkirakan oleh Hoed, bahwa hasil penafsiran penerjemah dapat berbeda dari maksud teks aslinya (hal. 33). Karenanya, sejumlah kata yang menyangkut aspek budaya dalam teks lama, perlu mendapat diberikan penjelasan agar tidak terjadi multitafsir lebih lanjut oleh para pembaca.
Jika teks lama bersumber dari manuskrip kuno ataupun prasasti, lain halnya dengan teks keagamaan yang bermula dari kitab suci agama yang ada di dunia. Tapi, teks keagamaan bukan hanya tentang kitab suci melulu. Teks keagamaan dapat mengacu pada teks-teks yang berbicara aspek keagamaan, seperti teologi. Penerjemah, ketika berhadapan dengan ini, tidak boleh mengurungkan niatnya hanya karena berbeda paham agama, atau mungkin saja ia menerjemahkannya dengan memasukkan alam ideologinya yang berbeda sekali dengan maksud teks tersebut. Justru sebaliknya, di saat itulah penerjemah dituntut untuk memahami teologi terlebih dahulu.
Utamanya, menurut Hoed dalam halaman 40, ada tiga hal yang harus diperhatikan saat hendak melakukan penerjemahan. Pertama, perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dengan kalimat lain, tidak ada dua bahasa yang sama, baik dari tata bahasanya, strukturnya, dan bahkan budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bahasa Arab dikenal adanya dualisme, yakni “mereka dua orang”. Tapi, dalam bahasa Indonesia, lebih dari satu orang pun sudah bisa dibilang “mereka”. Yang sering menjadi masalah bagi penerjemah bahasa Arab, adalah ketika menentukan diksi gender yang tepat dalam bahasa Indonesia. Umpamanya, dalam teks bahasa Arab ada beberapa kalimat yang terdapat kata “hiya”sebagai pronomina. Lalu, kadang kala di sinilah penerjemah mengalami kesulitan, apakah hiya tersebut nenek-nenek, gadis belia, atau guru wanita. Dalam masalah ini, penerjemah mesti menentukan padanan yang tepat.
Kedua, faktor konteks. Dengan menyelami konteks yang ada dalam teks, maka penerjemah pun akan mudah menerjemahkannya. Ketiga, prosedur penerjemahan. Setelah mengetahui konteks yang ada di dalam teks, penerjemah menentukan gaya penerjemahan seperti apa yang pantas dilakukan.
Dengan mengutip Newmark, Hoed memandang teks bukan sebagai sesatu yang bersifat statis. Tapi lebih dari itu, teks memiliki dinamika yang tertuang lama di sana. Kenapa? Karena teks juga dipengaruhi aspek luar bahasa yang terkadang kita melupakannya. Ada 10 faktor luar yang memengaruhi pemaknaan teks, 5 dari sisi teks asli, 5 lagi dari sisi teks terjemahan. Dari sisi teks asli: (1) penulis, (2) norma teks sumber, (3) kebudayaan, (4) setting (tempat dan waktu pemaknaan), (5) masyarakat pembaca teks asli. Dari sisi teks terjemahan: (6) norma teks terjemahan, (7) kebudayaan, (8) setting, (9) teks yang diterjemahkan tidak sesuai dengan latar keilmuan penerjemah, (10) pengetahuan penerjemah dapat memengaruhi terjemahan.
Buku ini pun memiliki perbedaan dengan buku penerjemahan lainnya. Di dalamnya dibahas soal kebudayaan dalam kaitannya dengan penerjemahan. Kebudayaan dapat menonjolkan dinamika penejemahan, dan akibatnya menjadikan penerjemah mengalami kesulitan. Inilah yang dikutip Hoed dari pendapat Nida (1966), karena menurutnya, faktor kebudayaan dapat menjadi kendala dalam penerjemahan.
Kebudayaan di tiap negara tentu berbeda. Karena perbedaan itu pula maka penerjemah akan menemukan sisi kebudayaan dari dua bahasa tersebut. Ketika menerjemah, terkadang bahasa yang diterjemahkan sulit dicari padanannya yang tepat untuk dapat dipahami dalam bahasa terjemahan. Oleh karena itu, para pakar di bidang penerjemahan sepakat bahwa seorang penerjemah akan melakukan perannya secara optimal jika ia menerjemahkan bahasa yang paling dikuasainya (hal. 81).
Hoed menjelaskan dua pokok masalah yang terkait dengan dua kebudayaan yang berbeda. Pertama, dalam bahasa Indonesia terdapat istilah-istilah budaya yang sulit dicari padanannya, seperti kebaya, batik, bupati, camat, terasi, lampu teplok, delman, bajigur, dan kredit candak kulak. Untuk mengantisipasinya, Hoed memberikan cara, yakni foreignization, dan domestication. Forensasi, merupakan cara menerjemah yang lebih memfokuskan alur terjemahannya pada bahasa yang diterjemah. Sedangkan domestikasi, cara menerjemah yang memfokuskan kepada bahasa sasaran dalam penerjemahan.
Forensasi dan domestikasi ini, amat terkait dengan ideologi dalam penerjemahan. Ideologi, dalam hal ini, tentang betul-salahnya suatu terjemahan, dan terjemahan apa yang terbaik untuk masyarakat pembaca. Penerjemah harus mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan digandrungi masyarakat. Karena kita pun tak bisa mengelak bahwa pembacalah yang menentukan keberterimaan suatu terjemahan. Dengan begitu, penerjemah dapat menentukan apakah kecenderungan terjemahan yang akan dihasilkannya lebih kepada bahasa sumber atau bahasa sasaran.
Karangan Hoed ini, membahas teori-teori penerjemahan dari segala aspek. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus yang sering menjadi perbincangan dalam masalah penerjemahan. Contoh-contoh dalam buku ini diberikan solusi, yang bisa dijadikan bahan acuan bagi penerjemah pemula. Hanya saja, contoh dalam buku ini lebih banyak menggunakan bahasa inggris, dibandingkan dengan bahasa lainnya, yang tentunya, menurut penulis dapat memperluas khazanah keilmuan bahasa kita.
Pada bagian pendahuluan bab ini, ditulis bukan oleh Hoed, tapi Alfons Taryadi. Bagian ini memaparkan apa saja yang bisa dikaitkan dengan ihwal penerjemahan. Penjelasan pada bagian ini memberitahukan kepada kita secara ringkas tentang kendala, faktor dalam penerjemahan, pemahaman teks sumber, dan ketiadaan terjemahan sempurna.
Seusai bagian pendahuluan, Hoed memulai tulisannya dengan mengungkapkan objek terjemahan, yaitu teks. Penerjemahan, seperti disinggung pada halaman 28, adalah upaya untuk mengungkapkan kembali pesan yang terkandung dalam teks suatu bahasa atau teks sumber ke dalam bentuk teks dalam bahasa lain atau teks sasaran. Dari situ, dapat dilihat bahwa teks merupakan bahasa itu sendiri. Syahdan, yang dihadapi penerjemah adalah bahasa, tepatnya dalam kaitan ini yakni bahasa tulis, teks.
Bahasa memiliki aspek bentuk dan makna. Dalam penerjemahan, aspek makna adalah pesan yang terkandung dalam bahasa sumber, atau bahasa yang diterjemahkan. Penulisnya-lah yang menciptakan pesan tersebut. Dan di sinilah tugas penerjemah untuk dapat mengalihkan pesan tersebut ke dalam bahasa lain.
Teks terjemahan bermacam-macam. Hanya saja, ada teks tertentu yang memiliki daya tersendiri bagi masyarakat. Teks lama dan teks keagamaan. Kedua teks ini memiliki keruwetan tersendiri, karena terkandung makna konteks sosial, yang bisa memunculkan efek sensitifitas. Teks lama sangat berkaitan dengan budaya masyarakat, dan teks keagamaan berkaitan dengan kepercayaan tiap pribadi manusia.
Teks lama, seperti manuskrip-manuskrip kuno yang jarak waktu pembuatannya amat jauh dari masa kini, memang memiliki nilai sejarah. Namun, di sisi lain, teks lama ini, apapun bentuknya, jika dikaitkan dengan penerjemahan, kompleksitas masalah pragmatiknya semakin bertambah. Seperti telah disinggung di atas, tentu ini dikarenakan adanya jarak waktu pembuatan teks lama tersebut, dengan penerjemah yang hidup di masa kini.
Akibatnya, kemungkinan besar akan muncul perbedaan tafsir di antara pembuat dan penerjemah teks lama. Karena bagaimana pun, jarak waktu dan jarak budaya amat berpengaruh bagi penerjemah. Inilah yang diperkirakan oleh Hoed, bahwa hasil penafsiran penerjemah dapat berbeda dari maksud teks aslinya (hal. 33). Karenanya, sejumlah kata yang menyangkut aspek budaya dalam teks lama, perlu mendapat diberikan penjelasan agar tidak terjadi multitafsir lebih lanjut oleh para pembaca.
Jika teks lama bersumber dari manuskrip kuno ataupun prasasti, lain halnya dengan teks keagamaan yang bermula dari kitab suci agama yang ada di dunia. Tapi, teks keagamaan bukan hanya tentang kitab suci melulu. Teks keagamaan dapat mengacu pada teks-teks yang berbicara aspek keagamaan, seperti teologi. Penerjemah, ketika berhadapan dengan ini, tidak boleh mengurungkan niatnya hanya karena berbeda paham agama, atau mungkin saja ia menerjemahkannya dengan memasukkan alam ideologinya yang berbeda sekali dengan maksud teks tersebut. Justru sebaliknya, di saat itulah penerjemah dituntut untuk memahami teologi terlebih dahulu.
Utamanya, menurut Hoed dalam halaman 40, ada tiga hal yang harus diperhatikan saat hendak melakukan penerjemahan. Pertama, perbedaan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran. Dengan kalimat lain, tidak ada dua bahasa yang sama, baik dari tata bahasanya, strukturnya, dan bahkan budayanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam bahasa Arab dikenal adanya dualisme, yakni “mereka dua orang”. Tapi, dalam bahasa Indonesia, lebih dari satu orang pun sudah bisa dibilang “mereka”. Yang sering menjadi masalah bagi penerjemah bahasa Arab, adalah ketika menentukan diksi gender yang tepat dalam bahasa Indonesia. Umpamanya, dalam teks bahasa Arab ada beberapa kalimat yang terdapat kata “hiya”sebagai pronomina. Lalu, kadang kala di sinilah penerjemah mengalami kesulitan, apakah hiya tersebut nenek-nenek, gadis belia, atau guru wanita. Dalam masalah ini, penerjemah mesti menentukan padanan yang tepat.
Kedua, faktor konteks. Dengan menyelami konteks yang ada dalam teks, maka penerjemah pun akan mudah menerjemahkannya. Ketiga, prosedur penerjemahan. Setelah mengetahui konteks yang ada di dalam teks, penerjemah menentukan gaya penerjemahan seperti apa yang pantas dilakukan.
Dengan mengutip Newmark, Hoed memandang teks bukan sebagai sesatu yang bersifat statis. Tapi lebih dari itu, teks memiliki dinamika yang tertuang lama di sana. Kenapa? Karena teks juga dipengaruhi aspek luar bahasa yang terkadang kita melupakannya. Ada 10 faktor luar yang memengaruhi pemaknaan teks, 5 dari sisi teks asli, 5 lagi dari sisi teks terjemahan. Dari sisi teks asli: (1) penulis, (2) norma teks sumber, (3) kebudayaan, (4) setting (tempat dan waktu pemaknaan), (5) masyarakat pembaca teks asli. Dari sisi teks terjemahan: (6) norma teks terjemahan, (7) kebudayaan, (8) setting, (9) teks yang diterjemahkan tidak sesuai dengan latar keilmuan penerjemah, (10) pengetahuan penerjemah dapat memengaruhi terjemahan.
Buku ini pun memiliki perbedaan dengan buku penerjemahan lainnya. Di dalamnya dibahas soal kebudayaan dalam kaitannya dengan penerjemahan. Kebudayaan dapat menonjolkan dinamika penejemahan, dan akibatnya menjadikan penerjemah mengalami kesulitan. Inilah yang dikutip Hoed dari pendapat Nida (1966), karena menurutnya, faktor kebudayaan dapat menjadi kendala dalam penerjemahan.
Kebudayaan di tiap negara tentu berbeda. Karena perbedaan itu pula maka penerjemah akan menemukan sisi kebudayaan dari dua bahasa tersebut. Ketika menerjemah, terkadang bahasa yang diterjemahkan sulit dicari padanannya yang tepat untuk dapat dipahami dalam bahasa terjemahan. Oleh karena itu, para pakar di bidang penerjemahan sepakat bahwa seorang penerjemah akan melakukan perannya secara optimal jika ia menerjemahkan bahasa yang paling dikuasainya (hal. 81).
Hoed menjelaskan dua pokok masalah yang terkait dengan dua kebudayaan yang berbeda. Pertama, dalam bahasa Indonesia terdapat istilah-istilah budaya yang sulit dicari padanannya, seperti kebaya, batik, bupati, camat, terasi, lampu teplok, delman, bajigur, dan kredit candak kulak. Untuk mengantisipasinya, Hoed memberikan cara, yakni foreignization, dan domestication. Forensasi, merupakan cara menerjemah yang lebih memfokuskan alur terjemahannya pada bahasa yang diterjemah. Sedangkan domestikasi, cara menerjemah yang memfokuskan kepada bahasa sasaran dalam penerjemahan.
Forensasi dan domestikasi ini, amat terkait dengan ideologi dalam penerjemahan. Ideologi, dalam hal ini, tentang betul-salahnya suatu terjemahan, dan terjemahan apa yang terbaik untuk masyarakat pembaca. Penerjemah harus mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan dan digandrungi masyarakat. Karena kita pun tak bisa mengelak bahwa pembacalah yang menentukan keberterimaan suatu terjemahan. Dengan begitu, penerjemah dapat menentukan apakah kecenderungan terjemahan yang akan dihasilkannya lebih kepada bahasa sumber atau bahasa sasaran.
Karangan Hoed ini, membahas teori-teori penerjemahan dari segala aspek. Buku ini juga dilengkapi dengan studi kasus yang sering menjadi perbincangan dalam masalah penerjemahan. Contoh-contoh dalam buku ini diberikan solusi, yang bisa dijadikan bahan acuan bagi penerjemah pemula. Hanya saja, contoh dalam buku ini lebih banyak menggunakan bahasa inggris, dibandingkan dengan bahasa lainnya, yang tentunya, menurut penulis dapat memperluas khazanah keilmuan bahasa kita.
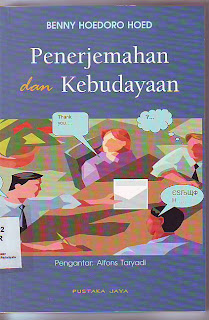
Comments